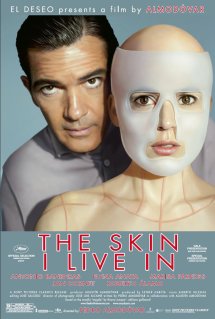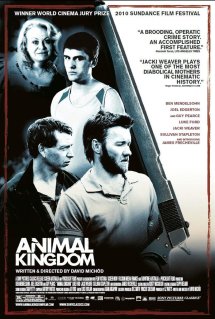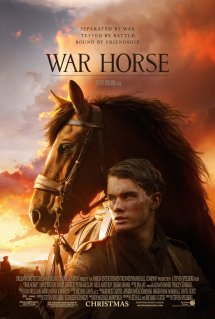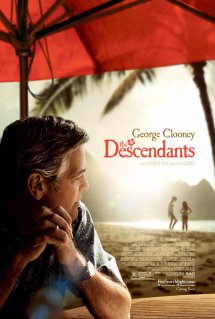Alasan saya menonton film ini adalah karena penasaran dengan akting Michael Shannon yang mencengangkan ketika berperan sebagai tetangga berpenyakit mental dari pasangan progresif (diperankan) DiCaprio-Winslet dalam Revolutionary Road. Apakah dalam film terbarunya ini ia juga memerankan karakter secara mendalam? Lewat drama thriller psikologis ala Stephen King, kita akan menjawab pertanyaan itu.
Take Shelter berkisah seorang pria yang mendapati tanda-tanda dilusif, halusinatif, dan semacamnya atas kejadian musibah tornado dahsyat yang akan melanda. Awalnya, ia dihantui dengan mimpi-mimpi buruk yang menurut saya secara sukses dikemas si strada sebagai suguhan mencekam. Ada satu adegan, bahkan, yang memaksa saya untuk buang muka dari layar monitor. Sejak merasakan tanda-tanda itu, hidupnya berangsur kacau. Kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya.
Sebenarnya, film ini terlanjur membosankan di bagian awalnya. Tak ada kaitan kuat, sama sekali. Namun justru dengan pertanyaan tentang mau apa sih nih film, malah secara tak langsung menyedot penonton dalam pusaran wahana halilintar yang siap menghempas dada. Pasalnya, yang menjadi masalah adalah film ini terlalu paham dengan apa yang dirasakan seorang bepenyakit mental sehingga nampaknya akan cukup susah jika membuat penonton “normal” berempati terhadap si karakter utama.
Begitulah adanya dengan film, seringkali kita merasa mengada-ada namun padahal bagi sebagian yang lainnya benar-benar terepresentasikan. Salut untuk kualitas akting Michael Shannon yang sampai film ini dirilis selalu sukses besar memerankan karakter psikis kurang mental sehat. [B] 20/02/12
Selasa, 21 Februari 2012
Resensi Film: Bad Education (2004)
Setelah The Skin I Live In, tak jauh-jauh saya masih menikmati karya Pedro Almodovar yang (lagi-lagi) berkutat ihwal identitas dan seks dalam selimut drama kriminal. Bad Education bercerita tentang seseorang pria yang masa lalunya mengalami salah asuhan di sekolah. Kenapa salah asuhan? Ya karena semasa masih mengenyam pendidikan dasar di seminari Katolik, ia “dikerjai” oleh gurunya dan ia menemukan cinta pertama nan terlarang. Langsung saja saya katakan, apa yang telah dialami si bocah yakni kasus pedofilia terselubung oleh seorang guru dan ia naksir dengan teman sesama jenis. Nah, semuanya itu nantinya akan terjalin dalam cerita utuh berkerangka sebuah labirin kriminalitas.
Yang saya bingungkan setelah menonton film adalah mengapa MPAA (lembaga penentu level usia di USA) memberi rating NC-17 terhadap film ini? Padahal sepanjang film tak ada adegan frontal seks dan organ-organ vital. Yah, terserah merekalah. Yang jelas dengan level NC-17 tentu saja jangkauan jumlah penontonnya akan lebih menciut. Satu-satunya yang bisa dipahami kenapa Bad Education dikasih rating NC-17 adalah karena materi filmnya yang “cukup” tabu dibicarakan karena terkait otoritas religi.
Baiklah, dibanding dengan karya terakhirnya The Skin I Live In, jelas Bad Education bukan pantaran. Alurnya tetap Almodovar banget yang ciamik dan jempolan dalam membedah cerita kilas lalu (flashback). Tapi yang menarik dalam film ini adalah sorotan pesan moralnya terhadap kaum termarjinalkan secara sosial. Film ini tak bercerita tentang segala kepedihan transgender, namun juga menampilkan porsi kewajaran seperti gagasan tentang anggota keluarga yang menyimpang tetaplah bagian dari keluarga. Di samping itu, film ini menegaskan lagi apa jadinya pendidikan jika pendidiknya tak kuasa menahan gairah bejat diri. [B] 19/02/12
Yang saya bingungkan setelah menonton film adalah mengapa MPAA (lembaga penentu level usia di USA) memberi rating NC-17 terhadap film ini? Padahal sepanjang film tak ada adegan frontal seks dan organ-organ vital. Yah, terserah merekalah. Yang jelas dengan level NC-17 tentu saja jangkauan jumlah penontonnya akan lebih menciut. Satu-satunya yang bisa dipahami kenapa Bad Education dikasih rating NC-17 adalah karena materi filmnya yang “cukup” tabu dibicarakan karena terkait otoritas religi.
Baiklah, dibanding dengan karya terakhirnya The Skin I Live In, jelas Bad Education bukan pantaran. Alurnya tetap Almodovar banget yang ciamik dan jempolan dalam membedah cerita kilas lalu (flashback). Tapi yang menarik dalam film ini adalah sorotan pesan moralnya terhadap kaum termarjinalkan secara sosial. Film ini tak bercerita tentang segala kepedihan transgender, namun juga menampilkan porsi kewajaran seperti gagasan tentang anggota keluarga yang menyimpang tetaplah bagian dari keluarga. Di samping itu, film ini menegaskan lagi apa jadinya pendidikan jika pendidiknya tak kuasa menahan gairah bejat diri. [B] 19/02/12
Selasa, 14 Februari 2012
Resensi Film: The Skin I Live In (2011)
Sinopsis film ini tak hanya membicarakan ihwal seorang dokter bedah transplantasi ahli yang sedang bereksperimen. Jauh, sangat jauh sekali dari ide sesederhana itu. Tapi sebagai tolak awal ceritanya, boleh deh kita memulainya dari situ. Si dokter yang diperankan secara dingin oleh Antonio Banderas itu menyimpan misteri masa lalu yang siap membuat penonton terpaku selama 2 jam guna menguak segala tabir.
Si dokter merawat intensif seorang pasien cewek di dalam rumah kliniknya. Bersama sang Ibu, si dokter terus mengawasi perkembangan si pasien yang sedang menjalani percobaan transplantasi kulit. Awalnya memang serba tak jelas memang alasan apa saja yang membuat pasien tersebut dikurung dalam sebuah kamar mewah dengan isolasi yang cukup ketat, tentunya selain karena mereka sedang dalam misi eksperimen tertutup. Namun makin ke belakang, makin karuanlah identitas si pasien dan rencana si dokter.
Alur cerita film ini maju-mundur, tapi jangan khawatir karena penanda masanya jelas dan mudah dipahami. Yang cukup kurang mudah dipahami adalah sejarah si dokter itu sendiri karena secara agak mengejutkan, khususnya bagi saya, tersibak dalam bagian jelang pungkasan film. Tentu ini menjadi kehebatan Pedro Almodovar sebagai strada mampu membungkus karya drama thriller-nya secara rapi dan mengecoh akselerasi mekanisme tebakan penonton.
Ternyata setelah film selesai, kita baru tahu banyak pesan moral yang ingin disampaikan oleh Almodovar. Atas nama keseruan, saya tak akan singkap apa saja pesan moral itu dalam ulasan ini. Yang jelas, film ini menjelaskan tentang kulit tubuh kita—sebagai hardware—penutup dari jiwa—sebagai software—yang tak bakal bisa ditukarkan oleh apapun itu bagaimanapun caranya. Inilah tontonan kritis pereaksi sikap egosentrisme manusia. [B/A] 11/02/12
Si dokter merawat intensif seorang pasien cewek di dalam rumah kliniknya. Bersama sang Ibu, si dokter terus mengawasi perkembangan si pasien yang sedang menjalani percobaan transplantasi kulit. Awalnya memang serba tak jelas memang alasan apa saja yang membuat pasien tersebut dikurung dalam sebuah kamar mewah dengan isolasi yang cukup ketat, tentunya selain karena mereka sedang dalam misi eksperimen tertutup. Namun makin ke belakang, makin karuanlah identitas si pasien dan rencana si dokter.
Alur cerita film ini maju-mundur, tapi jangan khawatir karena penanda masanya jelas dan mudah dipahami. Yang cukup kurang mudah dipahami adalah sejarah si dokter itu sendiri karena secara agak mengejutkan, khususnya bagi saya, tersibak dalam bagian jelang pungkasan film. Tentu ini menjadi kehebatan Pedro Almodovar sebagai strada mampu membungkus karya drama thriller-nya secara rapi dan mengecoh akselerasi mekanisme tebakan penonton.
Ternyata setelah film selesai, kita baru tahu banyak pesan moral yang ingin disampaikan oleh Almodovar. Atas nama keseruan, saya tak akan singkap apa saja pesan moral itu dalam ulasan ini. Yang jelas, film ini menjelaskan tentang kulit tubuh kita—sebagai hardware—penutup dari jiwa—sebagai software—yang tak bakal bisa ditukarkan oleh apapun itu bagaimanapun caranya. Inilah tontonan kritis pereaksi sikap egosentrisme manusia. [B/A] 11/02/12
Rabu, 08 Februari 2012
Resensi Film: Animal Kingdom (2010)
“It’s a crazy f*ckin’ world”
Itulah ucapan terakhir dalam film ini. Apa maksudnya? Yah setidaknya, kita akan mengamini ketika menonton Animal Kingdom. Jangan kira ini sebuah film dokumenter fauna lantaran judulnya yang berarti Kerajaan Binatang. Kerajaan disini berarti keluarga, sedangkan binatang maksudnya kriminal. Saya lupa darimana saya dapat referensi film ini, tapi yang jelas cukup mengejutkan karena sempat di luar dugaan.
Sebuah karya dari benua kangguru, sebelumnya saya jarang menonton film asal Aussie, yang menceritakan sebuah keluarga pelaku-kriminal sedang terombang-ambing karena satu per satu anggota “klub”-nya dihabisi polisi. Rentetan kejadian ini terjadi ketika keluarga tersebut ketambahan seorang keponakan di bawah 18 tahun yang ditinggal mati overdosis ibunya. Sejak awal kita dijejali informasi bahwa keluarga besar si keponakan memang tak beres. Terjebaklah ia pada situasi tersudut antara memilih membela keluarga “bejat” atau membuat pengakuan jujur yang akan menjebloskan hampir seluruh satu-satunya keluarga dekat yang tersisa ke sel tahanan. Pesan moral dalam kasus ini adalah “sejak awal jika memungkinkan jangan sekali-kali coba masuk ke lingkungn hitam”.
Saya sebenarnya tak terlalu tertarik dengan ide utama cerita film ini. Namun, nuansanya yang kuat membuat saya sempat berkeringat, terutama dalam adegan pengejaran tak menggebu-gebu namun gemas penuh endapan amarah. Akting para pemainnya walupun tak spesial, bisa dibilang cukup menyokong bangunan kelam. Yang membuat jengkel, saya berasa ikutan lomba tangkap belut atas plot psikologis karakter utamanya, si keponakan. Memancing tebakan-tebakan mau ke mana ia berpihak. Hingga akhir film, saya selalu telat menebaknya. Satu karya tak terkenal yang patut diperhitungkan. [B] 07/02/12
Itulah ucapan terakhir dalam film ini. Apa maksudnya? Yah setidaknya, kita akan mengamini ketika menonton Animal Kingdom. Jangan kira ini sebuah film dokumenter fauna lantaran judulnya yang berarti Kerajaan Binatang. Kerajaan disini berarti keluarga, sedangkan binatang maksudnya kriminal. Saya lupa darimana saya dapat referensi film ini, tapi yang jelas cukup mengejutkan karena sempat di luar dugaan.
Sebuah karya dari benua kangguru, sebelumnya saya jarang menonton film asal Aussie, yang menceritakan sebuah keluarga pelaku-kriminal sedang terombang-ambing karena satu per satu anggota “klub”-nya dihabisi polisi. Rentetan kejadian ini terjadi ketika keluarga tersebut ketambahan seorang keponakan di bawah 18 tahun yang ditinggal mati overdosis ibunya. Sejak awal kita dijejali informasi bahwa keluarga besar si keponakan memang tak beres. Terjebaklah ia pada situasi tersudut antara memilih membela keluarga “bejat” atau membuat pengakuan jujur yang akan menjebloskan hampir seluruh satu-satunya keluarga dekat yang tersisa ke sel tahanan. Pesan moral dalam kasus ini adalah “sejak awal jika memungkinkan jangan sekali-kali coba masuk ke lingkungn hitam”.
Saya sebenarnya tak terlalu tertarik dengan ide utama cerita film ini. Namun, nuansanya yang kuat membuat saya sempat berkeringat, terutama dalam adegan pengejaran tak menggebu-gebu namun gemas penuh endapan amarah. Akting para pemainnya walupun tak spesial, bisa dibilang cukup menyokong bangunan kelam. Yang membuat jengkel, saya berasa ikutan lomba tangkap belut atas plot psikologis karakter utamanya, si keponakan. Memancing tebakan-tebakan mau ke mana ia berpihak. Hingga akhir film, saya selalu telat menebaknya. Satu karya tak terkenal yang patut diperhitungkan. [B] 07/02/12
Minggu, 05 Februari 2012
Resensi Film: Margin Call (2011)
Saya bakal tak panjang lebar membahas film ini karena jujur saya tak begitu paham dengan dialog di dalamnya. Subtitle yang saya baca berbahasa Inggris, saya piker kalaupun saya dapat terjemahan bahasa Indonesia-nya tetap saja akan tak banyak mengubah. Saya suka memperhatikan film pertama-tama lewat judulnya. Ada dua kemungkinan dengan kata “Margin”. Pertama, nama seseorang dan kedua, “keuntungan”. Dan ternyata film ini tentang kemungkinan yang kedua.
Bertabur bintang kuat di film ini, sebut saja Jeremy Irons, Kevin Spacey, Paul Bettany, dan Demi Moore. Mereka melakukan tugas pemeranan secara cerdas. Salah satu kekuatan film ini ya terletak pada kualitas akting para karakternya. Hal lain yang penting adalah intensitas ketegangan yang terbangun lewat sinematografi dominasi malam hari dan plot berset waktu lebih kurang genap sehari penuh. Jangan dilupakan musik latar walaupun sederhana dan berulang-ulang tapi atmosferik seperti kita sedang menonton adegan eliminasi Indonesian Idol atau menanti jawaban benar/salah dalam Who Wants to be A Millionaire.
Oke, sekarang kisahnya. Kenapa saya tak begitu paham karena terlampau detail bahasa teknis ekonomi dalam film ini. Yang jelas menggambarkan bagaimana gentingnya gejolak ekonomi berbasis kapitalistik yang menjual/belikan aset dalam bentuk angka. Dalam sehari sebuah firma bisa memecat banyak pegawai tanpa menghiraukan lama masa kerja dan kontribusi, apalagi unsur humanis. Dalam waktu yang sehari pula semua bisa berubah, dari aman menjadi terancam. Nasib bisa berubah dalam hitungan jam, makanya mereka kadang bisa bekerja tanpa menghiraukan waktu istirahat. Uang melimpah, hidup tak tenang. Itulah yang ingin pula disampaikan Margin Call.
Panggilan laba menuntut manusia menjadi robot. Mencerabut manusia dari akarnya sehingga memandang manusia normal sebagai manusia abnormal. Satu film nondrama konvensional yang menegangkan! [B] 05/02/2012
Bertabur bintang kuat di film ini, sebut saja Jeremy Irons, Kevin Spacey, Paul Bettany, dan Demi Moore. Mereka melakukan tugas pemeranan secara cerdas. Salah satu kekuatan film ini ya terletak pada kualitas akting para karakternya. Hal lain yang penting adalah intensitas ketegangan yang terbangun lewat sinematografi dominasi malam hari dan plot berset waktu lebih kurang genap sehari penuh. Jangan dilupakan musik latar walaupun sederhana dan berulang-ulang tapi atmosferik seperti kita sedang menonton adegan eliminasi Indonesian Idol atau menanti jawaban benar/salah dalam Who Wants to be A Millionaire.
Oke, sekarang kisahnya. Kenapa saya tak begitu paham karena terlampau detail bahasa teknis ekonomi dalam film ini. Yang jelas menggambarkan bagaimana gentingnya gejolak ekonomi berbasis kapitalistik yang menjual/belikan aset dalam bentuk angka. Dalam sehari sebuah firma bisa memecat banyak pegawai tanpa menghiraukan lama masa kerja dan kontribusi, apalagi unsur humanis. Dalam waktu yang sehari pula semua bisa berubah, dari aman menjadi terancam. Nasib bisa berubah dalam hitungan jam, makanya mereka kadang bisa bekerja tanpa menghiraukan waktu istirahat. Uang melimpah, hidup tak tenang. Itulah yang ingin pula disampaikan Margin Call.
Panggilan laba menuntut manusia menjadi robot. Mencerabut manusia dari akarnya sehingga memandang manusia normal sebagai manusia abnormal. Satu film nondrama konvensional yang menegangkan! [B] 05/02/2012
Resensi Film: War Horse (2011)
Lagi, salah satu nomine film terbaik Oscar besutan maestro fiksi ilmiah, Steven Spielberg. Film ini memiliki material dasar potensial. Ceritanya entahlah terinspirasi dari kisah nyata atau tidak, tapi yang jelas di akhir penutup tak ada alinea pernyataan film ini fiksi seperti biasanya, menyulut heroisme penggugah semangat. Apabila penontonnya tersentuh, maka itulah bonusnya. Seekor kuda lelangan yang berhasil dibeli petani miskin di daerah terpencil Inggris era awal abad ke-20 menjadi representasi “kecil melawan besar”, “lemah melawan kuat”, dan “keteguhan hati”. Ia menandai gengsi kaum jelata yang merasa ada kalanya menggertak dan menantang.
Kuda itu dinamai Joey oleh putera si pembeli kuda lelangan dengan harga supertinggi. Apa yang dilakukan oleh sang ayah saat itu dinilai hal gila oleh sang isteri karena harganya yang terlampau tinggi, hingga harus berhutang, bahkan mempertaruhkan seluruh harta kekayaan. Sang ayah mulai gamang, namun tidak berlaku bagi Albert, si putera yang siap melatih Joey sebagai penarik bajak tanah. Lambat dan lamat, Joey menampilkan keistimewaannya. Ia setia dan teguh. Albert dan Joey terikat satu sama lain. Namun tragedi demi tragedi siap menjelang, terlebih lagi masa yang sedang mereka alami adalah era Perang Dunia I. Joey terpaksa dijual sebagai kuda perang lantaran gagal panen sehingga sang ayah tak mampu membayar hutang. Maka terpisahlah Albert dan Joey…
Sekilas nampak jelas bahwa kisah Joey menarik, bukan? Banyak sebenarnya film-film sejenis yakni dengan kuat secara sendirinya hanya dengan (bahkan) membaca sinopsis. Dulu saya juga pernah merinding membaca sinopsis Rindu Kami Pada-Mu arahan Garin. Tak ada PR wajib bagi Spielberg sebenarnya, tapi oleh karena dia seorang maestro dengan seabreg karya berkualitas maka wajar pula penonton berharap lebih dari sekadar standarnya. Lalu, bagaimana dengan War Horse? Bagi saya, semua formula standar sudah sangat baik diterapkan. Hanya saja memang tak ada kebaruan di sini. Musik pengiring yang biasanya John Williams menggarap secara monumental pun terdengar biasa saja bagi saya. Yang jelas, dalam War Horse strada Spielberg coba mengisi adegan-adegan yang belum sempat ia tuangkan dalam film-film perangnya terdahulu. Yah, semacam suplemen. Satu babak film yang menyerap dalam benak saya adalah ketika masing-masing seorang prajurit perang dari Inggris dan Jerman bertemu di tengah medan perang di antara parit-parit pasukan keduanya. Mereka saling bantu membebaskan Joey dari jeratan barikade kawat berduri. Dan perang pun berhenti ketika keduanya menolong Joey. Menyentuh. Sebenarnya masih ada lagi beberapa adegan yang menyentuh, tapi tenang saja karena War Horse bukan film jenis takziah.
Kuda perang itu kembali ke tuannya secara dramatis setelah jatuh ke tangan-tangan terkasih. Satu lagi film epos heroik dari Steven Spielberg. [B+] 05/02/2012
Kuda itu dinamai Joey oleh putera si pembeli kuda lelangan dengan harga supertinggi. Apa yang dilakukan oleh sang ayah saat itu dinilai hal gila oleh sang isteri karena harganya yang terlampau tinggi, hingga harus berhutang, bahkan mempertaruhkan seluruh harta kekayaan. Sang ayah mulai gamang, namun tidak berlaku bagi Albert, si putera yang siap melatih Joey sebagai penarik bajak tanah. Lambat dan lamat, Joey menampilkan keistimewaannya. Ia setia dan teguh. Albert dan Joey terikat satu sama lain. Namun tragedi demi tragedi siap menjelang, terlebih lagi masa yang sedang mereka alami adalah era Perang Dunia I. Joey terpaksa dijual sebagai kuda perang lantaran gagal panen sehingga sang ayah tak mampu membayar hutang. Maka terpisahlah Albert dan Joey…
Sekilas nampak jelas bahwa kisah Joey menarik, bukan? Banyak sebenarnya film-film sejenis yakni dengan kuat secara sendirinya hanya dengan (bahkan) membaca sinopsis. Dulu saya juga pernah merinding membaca sinopsis Rindu Kami Pada-Mu arahan Garin. Tak ada PR wajib bagi Spielberg sebenarnya, tapi oleh karena dia seorang maestro dengan seabreg karya berkualitas maka wajar pula penonton berharap lebih dari sekadar standarnya. Lalu, bagaimana dengan War Horse? Bagi saya, semua formula standar sudah sangat baik diterapkan. Hanya saja memang tak ada kebaruan di sini. Musik pengiring yang biasanya John Williams menggarap secara monumental pun terdengar biasa saja bagi saya. Yang jelas, dalam War Horse strada Spielberg coba mengisi adegan-adegan yang belum sempat ia tuangkan dalam film-film perangnya terdahulu. Yah, semacam suplemen. Satu babak film yang menyerap dalam benak saya adalah ketika masing-masing seorang prajurit perang dari Inggris dan Jerman bertemu di tengah medan perang di antara parit-parit pasukan keduanya. Mereka saling bantu membebaskan Joey dari jeratan barikade kawat berduri. Dan perang pun berhenti ketika keduanya menolong Joey. Menyentuh. Sebenarnya masih ada lagi beberapa adegan yang menyentuh, tapi tenang saja karena War Horse bukan film jenis takziah.
Kuda perang itu kembali ke tuannya secara dramatis setelah jatuh ke tangan-tangan terkasih. Satu lagi film epos heroik dari Steven Spielberg. [B+] 05/02/2012
Resensi Film: The Descendants (2011)
Ini dia film drama terbaik tahun 2011 versi Golden Globe bersanding dengan The Artist sebagai film musikal atau komedi terbaiknya. Sebelum keluar sebagai jawara pun saya sudah mengamati skornya hasil konsensus kritikus film. Lumayan tinggilah… Dengan berposterkan George Clooney berpakaian ala Hawai sedang duduk di bangku bawah payung peneduh menengok anak-anak yang berada jauh di belakangnya sedang bermain-main di bibir pantai, film ini mengundang tanya serta belum menampakkan jelas ide cerita secara keseluruhan. Malah lebih karuan jika posternya seperti sinetron-sinetron Indonesia (amit-amit, astaghfirullah…) macam Putri yang Ditukar dengan memajang semua pemain ayu-gantengnya membentuk pola barisan ujung panah. Biasanya yang terdepan merupakan pemain utamanya (baca: yang lagi baik daun Nikita Willy). Yang jenis-jenis poster macam ini barulah patut dicurigai dan dihindari.
Oh, ternyata The Descendants memang berujar seperti judulnya, yakni keturunan atau anak cucu. Bagaimana sih kelakuan dan dinamika hidup keturunan zaman sekarang? Lewat keluarga Clooney, penonton diajak menyoroti dan berdiskusi sekaligus. Karakter utama yang diperankan Clooney merupakan pemegang wali ahli waris dari keluarga besar campuran leluhur pribumi Hawai dan pendatang. Tanahnya mahaluas. Tak semua saudaranya sukses, ada pula yang doyannya menghabiskan uang. Tibalah pada saat keluarga ini dihadapkan pada tawaran menggiurkan nan menjanjikan. Akan dipertahankan atau dijualkah harta warisan mereka? Clooney memerankan karakter yang untuk ukuran konglomerat memilih hidup tak foya-foya, mandiri, tak ingin menyandarkan hidup dari warisan (nyindir para pengharap warisan bo’), makanya terkesan pelit. Bukan sebuah keputusan sulit sebenarnya untuk Clooney jika mengahadapi pilihan itu dalam kondisi normal, sekarang ia sedang dalam masalah berat…
Masalah itu menggelayut sejak awal film. Isteri-kurang-terperhatikan dari Clooney terbaring koma di rumah sakit karena kecelakaan motorboat. Kondisi ini menggiring Clooney pada suasana hati dan emosi yang gampang tergoyahkan. Belum lagi ketika diberi tahu vonis tanpa harapan dari dokter perawatnya. Mulailah plot perekat mengalir… Mengabari satu per satu keluarga dan teman dekat isterinya atas hal tersebut supaya ada kesempatan bagi mereka mengucap selamat tinggal. Ya ampun, adegan demi adegan setelahnya malah menari-nari menghempas penonton dari birunya rasa haru dan berkembang menjadi cerita komedi sekaligus pilu, ya ala Stephen Chow dalam dosis yang sangat rendah.
Komedi yang ditawarkan The Descendants cukup elegan karena ia berimbang. Maksudnya, tak hanya menertawakan orang lain tapi juga sekalian menertawakan diri sendiri. Menurut saya itu susah. Lihat saja dalam adegan ketika Clooney meluapkan emosi di depan isterinya yang terbaring koma, melampiaskan kemarahan kepada isterinya, namun kemudian merelakan bahkan memaafkan. Pada satu momen, manusia memang mendua (fase lebih ringan munafik). Ia mampu berani jujur sepenuhnya ketika lawan bicara tak kuasa membalas atau bereaksi. Situasi itu takkan mudah tercipta ketika dialog berjalan dalam kondisi normal.
Lewat perkawinan antara isu ketamakan manusia dengan menjual warisan, isu lingkungan dengan membiarkan alam apa adanya tanpa ditusuk-tusuk beton paku bumi, dan drama elegy dalam rumah tangga, The Descendants teracik sempurna pada takaran ringan. [B/A] 05/02/2012
Oh, ternyata The Descendants memang berujar seperti judulnya, yakni keturunan atau anak cucu. Bagaimana sih kelakuan dan dinamika hidup keturunan zaman sekarang? Lewat keluarga Clooney, penonton diajak menyoroti dan berdiskusi sekaligus. Karakter utama yang diperankan Clooney merupakan pemegang wali ahli waris dari keluarga besar campuran leluhur pribumi Hawai dan pendatang. Tanahnya mahaluas. Tak semua saudaranya sukses, ada pula yang doyannya menghabiskan uang. Tibalah pada saat keluarga ini dihadapkan pada tawaran menggiurkan nan menjanjikan. Akan dipertahankan atau dijualkah harta warisan mereka? Clooney memerankan karakter yang untuk ukuran konglomerat memilih hidup tak foya-foya, mandiri, tak ingin menyandarkan hidup dari warisan (nyindir para pengharap warisan bo’), makanya terkesan pelit. Bukan sebuah keputusan sulit sebenarnya untuk Clooney jika mengahadapi pilihan itu dalam kondisi normal, sekarang ia sedang dalam masalah berat…
Masalah itu menggelayut sejak awal film. Isteri-kurang-terperhatikan dari Clooney terbaring koma di rumah sakit karena kecelakaan motorboat. Kondisi ini menggiring Clooney pada suasana hati dan emosi yang gampang tergoyahkan. Belum lagi ketika diberi tahu vonis tanpa harapan dari dokter perawatnya. Mulailah plot perekat mengalir… Mengabari satu per satu keluarga dan teman dekat isterinya atas hal tersebut supaya ada kesempatan bagi mereka mengucap selamat tinggal. Ya ampun, adegan demi adegan setelahnya malah menari-nari menghempas penonton dari birunya rasa haru dan berkembang menjadi cerita komedi sekaligus pilu, ya ala Stephen Chow dalam dosis yang sangat rendah.
Komedi yang ditawarkan The Descendants cukup elegan karena ia berimbang. Maksudnya, tak hanya menertawakan orang lain tapi juga sekalian menertawakan diri sendiri. Menurut saya itu susah. Lihat saja dalam adegan ketika Clooney meluapkan emosi di depan isterinya yang terbaring koma, melampiaskan kemarahan kepada isterinya, namun kemudian merelakan bahkan memaafkan. Pada satu momen, manusia memang mendua (fase lebih ringan munafik). Ia mampu berani jujur sepenuhnya ketika lawan bicara tak kuasa membalas atau bereaksi. Situasi itu takkan mudah tercipta ketika dialog berjalan dalam kondisi normal.
Lewat perkawinan antara isu ketamakan manusia dengan menjual warisan, isu lingkungan dengan membiarkan alam apa adanya tanpa ditusuk-tusuk beton paku bumi, dan drama elegy dalam rumah tangga, The Descendants teracik sempurna pada takaran ringan. [B/A] 05/02/2012
Langganan:
Postingan (Atom)